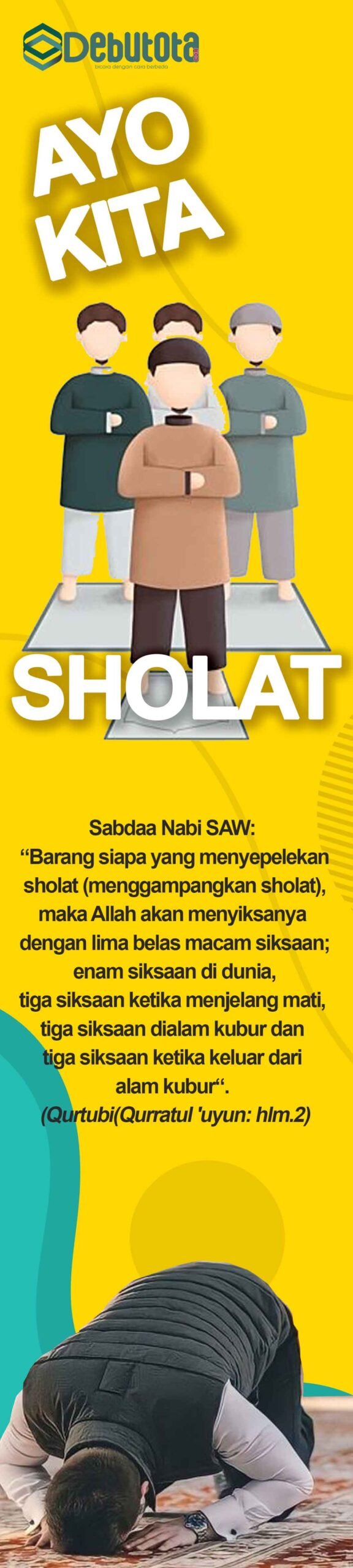BUTOTA – TAJUK | Desakan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk menonaktifkan Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, patut diapresiasi sebagai bentuk pengawasan legislatif. Namun, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga menuntut lebih dari sekadar desakan politis dan diperlukan landasan faktual dan prosedural yang kuat.
Pertama, substansi rekomendasi perlu dipertanyakan. Surat DPRD menyebut “hasil pembahasan dan penelaahan terhadap laporan pelaksanaan tugas”, namun tidak menjelaskan secara spesifik pelanggaran atau cacat kinerja yang menjadi dasar penonaktifan. Dalam sistem hukum administrasi, penonaktifan pejabat adalah tindakan serius yang memerlukan alasan konkret, bukan sekadar penilaian subjektif tentang “konduktifitas” atau “efektifitas” yang abstrak.
Penonaktifan pejabat struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 250 yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara dapat dilakukan dalam kondisi: (1) dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sementara; (2) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; (3) dituntut karena melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatan dan ancaman pidananya 2 tahun penjara atau lebih.
Lebih lanjut, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengamanatkan bahwa setiap keputusan pejabat harus berdasarkan fakta yang relevan dan pertimbangan yang rasional. Penonaktifan tanpa alasan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi cacat hukum dan dapat digugat melalui PTUN.
Pertanyaannya, apakah DPRD telah menyampaikan bukti bahwa Sekda memenuhi kriteria tersebut? Jika hanya soal perbedaan pandangan dalam komunikasi atau koordinasi kebijakan anggaran, hal itu adalah ranah diskursus normal dalam dinamika pemerintahan—bukan alasan untuk penonaktifan.
Berikutnya, soal proporsi dukungan. Meski 32 dari 40 anggota menandatangani, fakta bahwa 8 anggota menolak menunjukkan tidak ada konsensus bulat. Dalam isu strategis menyangkut jabatan kunci birokrasi, pembelahan suara ini seharusnya mendorong dialog lebih mendalam bukan tergesa memaksakan kehendak mayoritas.
Selanjutnya dari aspek prosedural, jika memang ada indikasi pelanggaran atau kelalaian tugas, mekanisme yang tepat adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk investigasi menyeluruh sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pansus bertugas melakukan kajian mendalam, mendengar keterangan pihak terkait, dan menyusun rekomendasi berbasis fakta.
Permintaan penonaktifan langsung tanpa proses investigasi formal berisiko menciderai prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan dapat menciptakan preseden buruk dalam hubungan eksekutif-legislatif. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga etika berdemokrasi.
Dari kacamata publik, desakan ini terkesan prematur dan menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, transparansi. Masyarakat belum mendapat penjelasan yang gamblang tentang apa kesalahan konkret Sekda. Jika hanya soal komunikasi atau koordinasi yang kurang lancar—seperti yang sempat diberitakan sebelumnya tentang penolakan Sekda membahas anggaran lewat telepon, ini adalah isu teknis yang bisa diselesaikan melalui rapat koordinasi, bukan dengan rekomendasi penonaktifan. Publik berhak tahu, apakah ada dugaan korupsi? Penyalahgunaan wewenang? Atau hanya perbedaan politik?
Kedua, timing yang mencurigakan. Desakan ini muncul di tengah proses pembahasan anggaran dan dinamika politik lokal yang tengah panas. Publik wajar bertanya bahwa apakah ini murni pengawasan kinerja, ataukah ada agenda politik tertentu? Jangan sampai institusi pengawasan digunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu, sementara rakyat yang dirugikan.
Ketiga, dampak terhadap birokrasi. Penonaktifan Sekda akan menimbulkan kekosongan kepemimpinan di jantung birokrasi daerah. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus berjalan, mulai dari pengelolaan APBD, koordinasi program pembangunan, hingga pelayanan administratif, kekosongan ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat.
Keempat, sinyal buruk bagi good governance. Jika setiap pejabat bisa dinonaktifkan hanya karena perbedaan pendapat atau gaya komunikasi, ini akan menciptakan kultur politik balas dendam dan ketidakpastian dalam birokrasi. Pejabat akan takut mengambil keputusan tegas, lebih memilih aman dan kompromi demi menjaga posisi dan bukan demi kepentingan publik.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi seharusnya merespons dengan kepala dingin. Menindaklanjuti rekomendasi bukan berarti harus patuh membabi buta, melainkan mengkaji secara objektif. Apakah ada basis hukum yang memadai? Apakah ada pelanggaran yang terbukti? Jika tidak, mempertahankan Sekda adalah keputusan yang sah dan bertanggung jawab.
Bupati Sofyan juga harus mengambil langkah terukur, dengan meminta klarifikasi tertulis kepada DPRD tentang dasar hukum dan fakta konkret yang menjadi alasan desakan penonaktifan. Kemudian, membuka ruang dialog dengan DPRD untuk menyelesaikan persoalan koordinasi dan komunikasi yang menjadi akar masalah, jika memang itu intinya. Melakukan penilaian internal terhadap kinerja Sekda secara objektif, melibatkan inspektorat daerah jika diperlukan.
Berikutnya, mengomunikasikan kepada publik secara terbuka tentang duduk persoalan sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Mempertahankan prinsip hukum, jika tidak ada bukti pelanggaran yang memenuhi syarat hukum, mempertahankan Sekda adalah keputusan yang sah dan bertanggung jawab.
Yang dibutuhkan bukan drama politik yang menguras energi dan mengalihkan fokus dari agenda pembangunan, melainkan klarifikasi terbuka tentang penilaian kinerja Sekda, dialog konstruktif antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan demi kepentingan masyarakat Gorontalo.
Demokrasi bukan soal siapa yang lebih keras bersuara, tapi siapa yang lebih kuat argumennya. Pengawasan legislatif harus berbasis fakta dan hukum, bukan asumsi dan kepentingan sesaat.
Kita juga berhak mendapat pemerintahan yang stabil, profesional, dan fokus pada pelayanan publik, bukan terjebak dalam pusaran politik berkepanjangan yang tidak produktif, apalagi inti masalah berbicara tentang hajat rakyat banyak yang memang dibutuhkan beragam dinamika yang tercipta secara dinamis. Dan bisa dipastikan, publik bisa menerka apa hasil akhir dari polemik ini. Sebab di 10 Tahun terakhir, Kabupaten Gorontalo diwarnai sandiwara akhir Tahun, yang ujung-ujungnya selesai dengan “cara” mereka sendiri. [***]