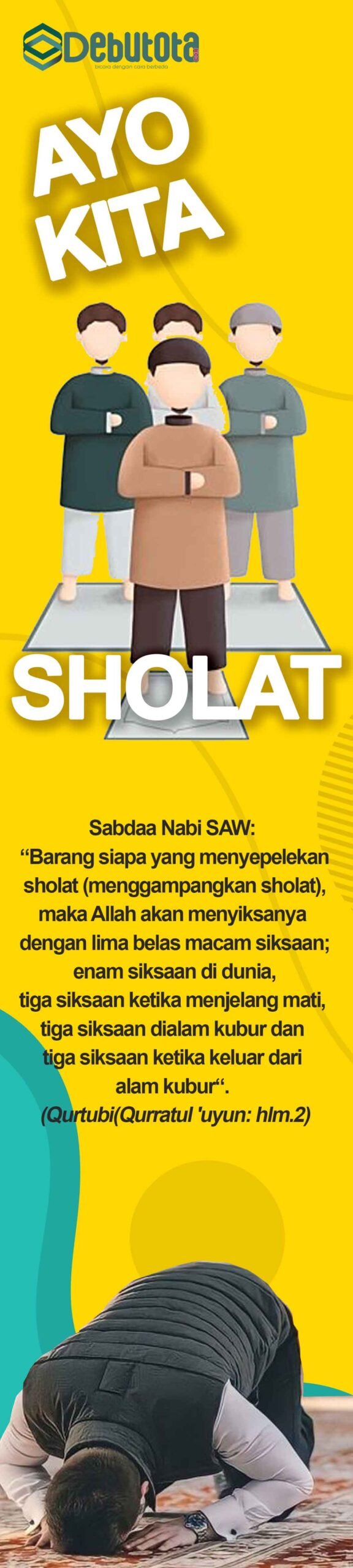BUTOTA – OPINI | Setiap 9 Februari, kita memperingati Hari Pers Nasional sebagai penanda kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta tahun 1946. Namun, memasuki tahun 2026 ini, peringatan tersebut terasa pahit di tenggorokan para insan pers. Sebab, realitas yang dihadapi wartawan di Indonesia hari ini justru mengingatkan kita bahwa kemerdekaan pers yang diperjuangkan sejak 80 tahun lalu, ternyata belum sepenuhnya merdeka.
Tahun 2025 mencatat sejarah kelam bagi kebebasan pers Indonesia. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) bahkan secara resmi menyatakan “darurat pembungkaman pers” menyusul rangkaian intimidasi, ancaman pembunuhan, kekerasan fisik, hingga kriminalisasi terhadap wartawan di berbagai daerah. Praktik premanisme, mafia ekonomi ilegal, oknum organisasi masyarakat, bahkan sesama insan pers yang menyimpang dari etika jurnalistik, masih secara terang-terangan berupaya membungkam kerja jurnalistik yang independen dan kritis.
Sebelumnya, pembacokan penulis sebagai Pemimpin Redaksi Butota, menjadi bukti nyata betapa berbahayanya profesi jurnalis di negeri ini. Pada Juni 2021, dibacok oleh orang tak dikenal hingga lengan nyaris putus. Serangan brutal ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi pesan intimidasi yang jelas: berhentilah mencari kebenaran, atau nyawamu taruhannya.
Cerita serupa terus berulang hingga kini. Di Lampung Selatan pada November 2025, wartawan Kompas TV Teuku Khalid Syah mendapat ancaman ditikam oleh sekelompok preman saat meliput dugaan pemerasan. Di Serang, Banten, pada Agustus 2025, delapan jurnalis mengalami kekerasan brutal saat meliput sidak Kementerian Lingkungan Hidup di PT Genesis Regeneration Smelting, diduga melibatkan oknum aparat keamanan. Di Bekasi, wartawan diintimidasi oleh preman saat mengklarifikasi pemberitaan tentang penipuan.
Bahkan lebih memprihatinkan, intimidasi juga datang dari aparat yang seharusnya melindungi warga negara. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mencatat berbagai kasus kekerasan pada 2025, termasuk ancaman dari ajudan Panglima TNI terhadap jurnalis Kompas.com, pemukulan jurnalis ProgreSIP oleh sekelompok orang berpakaian bebas yang diduga anggota polisi, hingga serangan terhadap wartawan Tempo di Semarang yang diduga dilakukan aparat berpakaian preman.
Yang lebih menyakitkan adalah ketika wartawan diperhadapkan atau bahkan diadu domba dengan masyarakat dengan dalih stabilitas daerah atau kepentingan kelompok tertentu. Ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, perusakan lingkungan, atau penyalahgunaan kekuasaan, wartawan sering dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai provokator atau perusak harmoni sosial.
Kasus ancaman pembunuhan terhadap Ketua DPD AKPERSI Banten, Yudianto, pada Juni 2025 oleh pelaku usaha mafia gas oplosan menunjukkan bagaimana jurnalis investigatif dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang memiliki kepentingan gelap. Di Bitung, Sulawesi Utara, pada Februari 2025, Ketua DPD AKPERSI Sulut mengalami intimidasi dan pemukulan oleh oknum anggota ormas, menunjukkan betapa rentannya posisi wartawan di daerah.
Pola yang sama terlihat di Majalengka, di mana awak media yang ingin melakukan kontrol publik terhadap proyek revitalisasi sekolah justru dihadang oleh oknum preman. Ini membuktikan bahwa ada upaya sistematis untuk membungkam pers dengan menggunakan kekerasan jalanan sebagai senjata.
Di Gorontalo, setiap pemberitaan yang sensitif tentang dugaan korupsi, beberapa pihak selalu memanfaatkan masyarakat untuk menindas dan menakut-nakuti wartawan yang bertugas untuk memberitakan persoalan dugaan korupsi, baik yang belum atau sementara ditangani aparat penegak hukum. Ekstrimnya, malah oknum aparat penegak hukum justru menghubungi wartawan untuk mendiami proses penanganan perkara korupsi.
Di tengah tekanan dan ancaman yang terus menghantui, solidaritas sesama wartawan menjadi pertanyaan krusial: apakah solidaritas yang kita miliki hanya tembang pilih, atau benar-benar menjadi kekuatan untuk melindungi dan membela sesama?
Fakta menunjukkan bahwa solidaritas wartawan di Indonesia masih rapuh dan terfragmentasi. Terlalu banyak organisasi pers dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada organisasi seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang lahir dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Orde Baru dan konsisten memperjuangkan independensi. Di sisi lain, muncul berbagai organisasi baru yang terkadang malah menambah perpecahan di tubuh pers sendiri.
Yang lebih menyedihkan, kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa sembilan media online melanggar kode etik dengan mencatut nama tanpa konfirmasi, dan oknum yang mengaku insan pers justru melakukan perendahan martabat terhadap sesama wartawan dengan sebutan “media receh” dan ancaman verbal. Ini membuktikan bahwa musuh terbesar pers bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam: dari mereka yang mengaku wartawan namun tidak menghormati etika profesi.
Di era global yang penuh dengan disinformasi dan tekanan dari berbagai pihak, wartawan di daerah masih menghadapi tekanan dan intervensi baik dari swasta maupun pemerintahan dan aparat. Mereka bekerja dalam keterbatasan sumber daya, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan sering kali tanpa dukungan dari sesama rekan seprofesi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lahir di era reformasi sebenarnya telah memberikan perlindungan yang jelas. Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Namun, penegakan hukum masih jauh dari harapan.
UU Pers 1999 lahir dari semangat reformasi untuk mengembalikan niat suci pers sebagaimana diperjuangkan para tokoh pers di masa lalu. Bahkan di era Soeharto yang represif, dengan segala keterbatasannya, tokoh-tokoh pers seperti mereka yang terlibat dalam deklarasi Sirnagalih 1994 tetap memperjuangkan kemerdekaan pers meski harus membayar mahal: Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dipenjara 3 tahun, Danang Kukuh Wardoyo 20 bulan, dan Andi Syahputra 18 bulan.
Niat suci pers adalah menjadi pilar keempat demokrasi, melakukan kontrol sosial, menyebarkan informasi yang benar kepada publik, dan memperjuangkan keadilan. Bukan menjadi corong kekuasaan, alat kepentingan kelompok, atau tukang ancam sesama wartawan.
Hari Pers Nasional 2026 ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan solidaritas sejati di tubuh pers Indonesia. Solidaritas bukan hanya slogan atau iklan di media sosial ketika ada kasus kekerasan, tetapi aksi nyata: saling melindungi, saling membela, dan bersatu melawan segala bentuk intimidasi.
Organisasi-organisasi pers harus mengesampingkan ego sektoral dan kepentingan kelompok. Kita butuh satu suara yang kuat untuk menuntut perlindungan hukum yang nyata bagi wartawan, penegakan UU Pers yang tegas terhadap pelaku intimidasi, dan mekanisme perlindungan wartawan yang sistematis terutama di daerah-daerah.
Pemerintah tidak boleh tutup mata. Ketika wartawan diserang, itu berarti demokrasi diserang. Ketika pers dibungkam, itu berarti hak publik untuk tahu dibungkam. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan, tanpa pandang bulu, bahkan jika pelakunya adalah oknum dari institusi mereka sendiri.
Solidaritas wartawan di era global ini harus menjadi kekuatan kolektif yang mampu melindungi setiap insan pers yang menjalankan fungsinya dengan integritas. Bukan solidaritas tembang pilih yang hanya untuk teman dekat atau kelompok tertentu, tetapi solidaritas universal untuk setiap wartawan yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik.
Kemerdekaan pers yang kita rayakan setiap 9 Februari masih jauh dari realisasi penuh. Masih banyak wartawan yang bekerja dalam ketakutan, masih banyak kebenaran yang terkubur karena intimidasi, masih banyak kepentingan publik yang terabaikan karena pers dibungkam.
Namun, semangat para tokoh pers di tahun 1946, semangat para pejuang kemerdekaan pers di era Orde Baru, dan semangat para perumus UU Pers 1999 harus terus menyala di dada setiap insan pers. Kemerdekaan pers bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan yang terus-menerus.
Di tahun 2026 ini, mari kita kembalikan niat suci pers bahw menjadi penjaga kebenaran, pengawal demokrasi, dan suara bagi mereka yang tak bersuara. Mari kita wujudkan solidaritas sejati yang menjadi benteng perlindungan bagi setiap wartawan yang berani mengungkap kebenaran, sebagaimana semangat pers sebagai pilr keempat demokrasi.
Karena pers yang merdeka adalah pers yang berani, pers yang berani membutuhkan perlindungan, dan perlindungan terbaik adalah solidaritas yang sejati.
“Dirgahayu Hari Pers Nasional ke-80. Merdeka atau Mati!”

Oleh : Jeffry As. Rumampuk [Pimpinan Butota Media Group]
Catatan: Artikel ini ditulis sebagai refleksi kritis terhadap kondisi kebebasan pers di Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2026